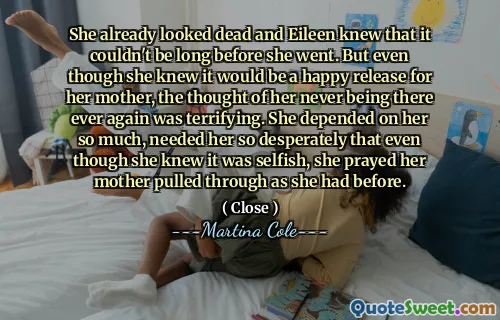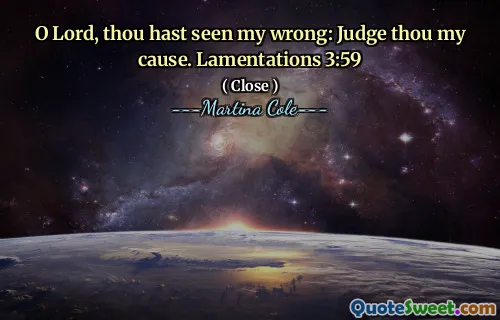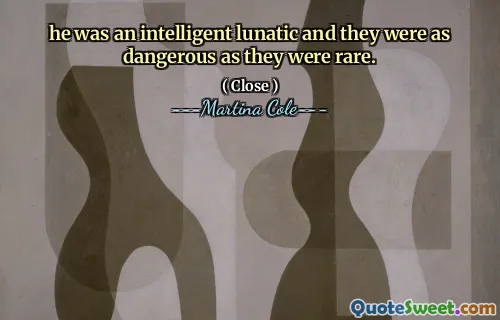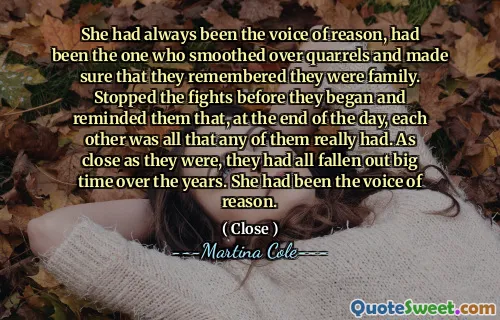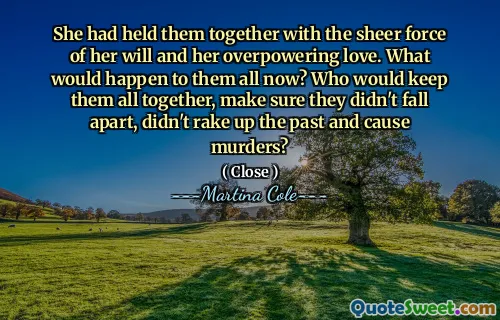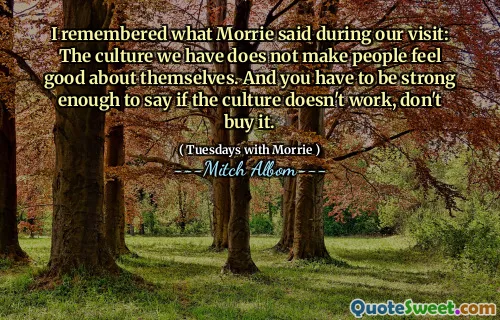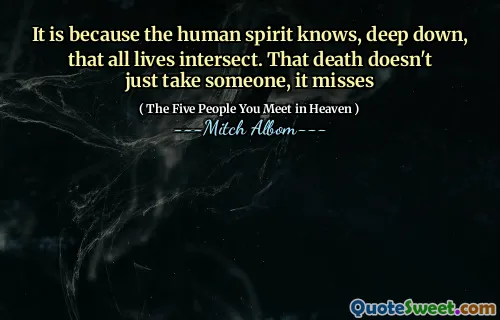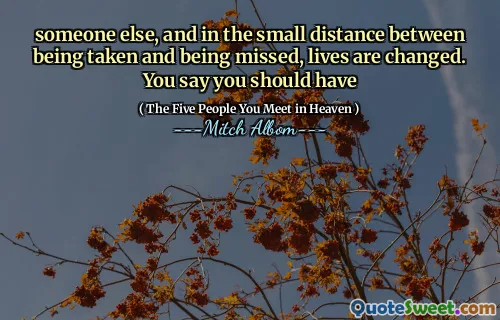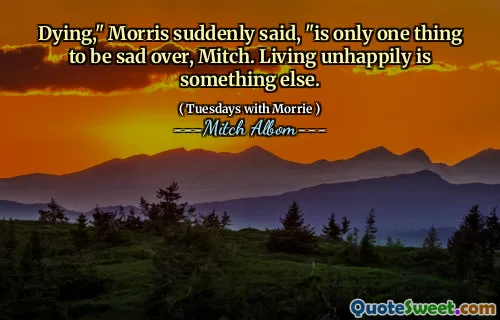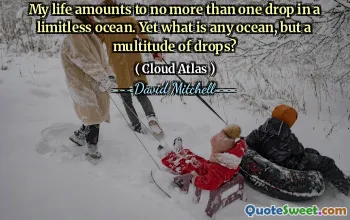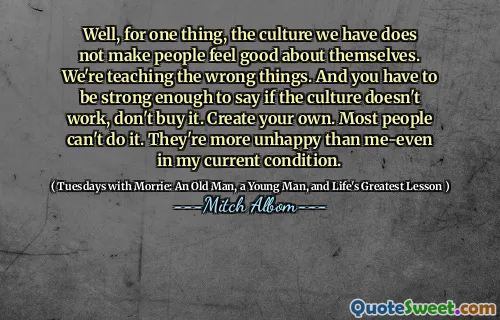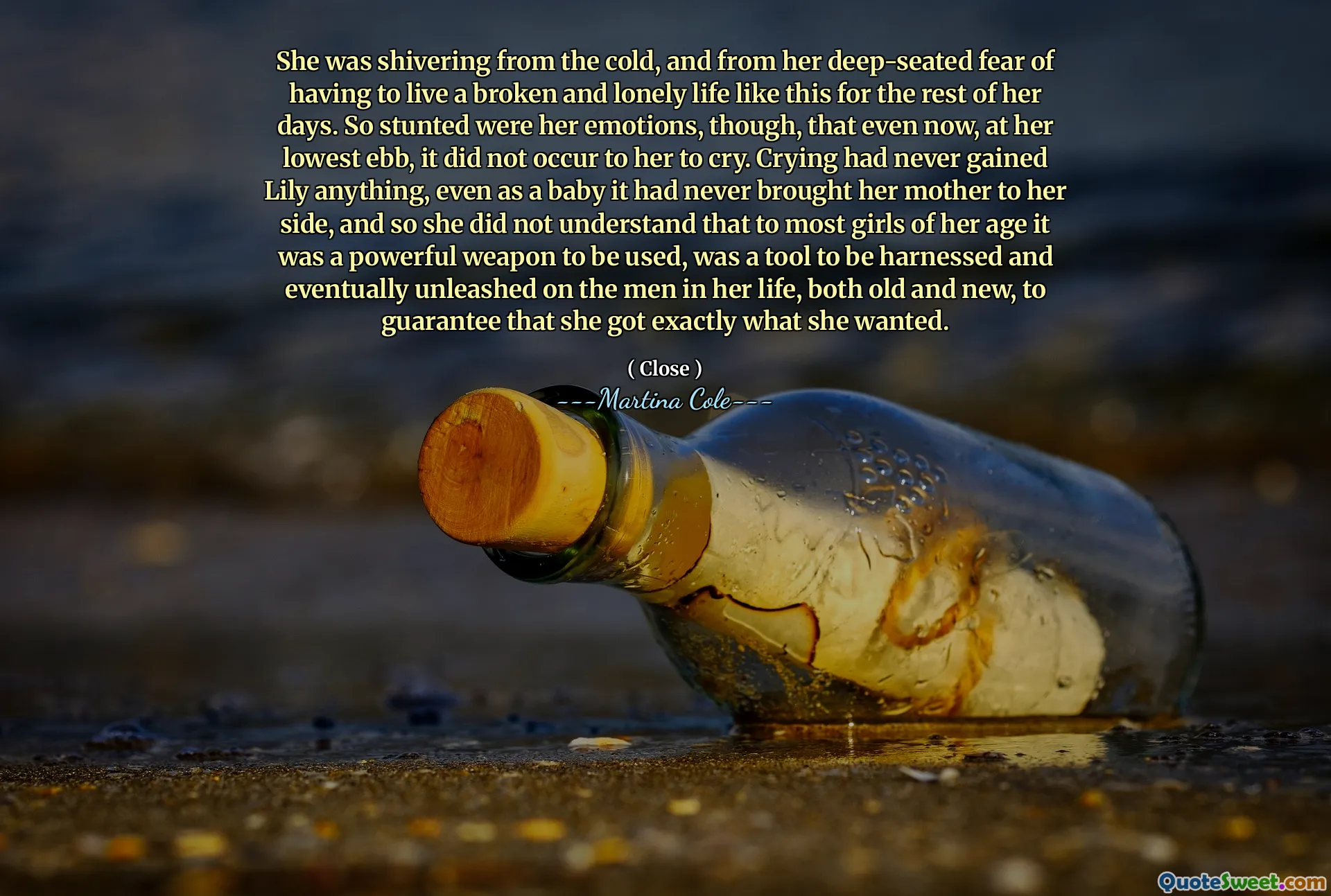
Dia menggigil dari kedinginan, dan dari ketakutannya yang mendalam karena harus menjalani kehidupan yang hancur dan sepi seperti ini selama sisa hari-harinya. Namun, terhambatnya emosinya, sehingga bahkan sekarang, di pasang surut terendahnya, tidak terpikir olehnya untuk menangis. Menangis tidak pernah mendapatkan Lily apa pun, bahkan ketika bayi itu tidak pernah membawa ibunya ke sisinya, dan dia tidak mengerti bahwa bagi kebanyakan gadis seusianya, itu adalah senjata yang kuat untuk digunakan, adalah alat untuk dimanfaatkan dan akhirnya melepaskan pria dalam hidupnya, baik tua maupun baru, untuk menjamin bahwa dia mendapatkan apa yang dia inginkan.
(She was shivering from the cold, and from her deep-seated fear of having to live a broken and lonely life like this for the rest of her days. So stunted were her emotions, though, that even now, at her lowest ebb, it did not occur to her to cry. Crying had never gained Lily anything, even as a baby it had never brought her mother to her side, and so she did not understand that to most girls of her age it was a powerful weapon to be used, was a tool to be harnessed and eventually unleashed on the men in her life, both old and new, to guarantee that she got exactly what she wanted.)
Lily mengalami kedinginan dan ketakutan yang mendalam, merasa terjebak dalam kehidupan kesepian dan keputusasaan. Meskipun berada di titik terendahnya, dia terhambat secara emosional; Pikiran menangis bahkan tidak terlintas di benaknya. Sepanjang hidupnya, air matanya tidak pernah menarik perhatian yang dia butuhkan, terutama dari ibunya, membawanya untuk percaya bahwa menangis tidak efektif.
Kebanyakan gadis seusianya melihat air mata sebagai alat yang berharga untuk manipulasi dan ekspresi emosional, tetapi Lily tidak menyadari hal ini. Tidak seperti mereka, dia tidak pernah belajar memanfaatkan emosinya untuk mempengaruhi orang -orang di sekitarnya, membuatnya terisolasi dalam perjuangannya dan tidak dapat mengekspresikan kebutuhan atau keinginannya secara efektif.